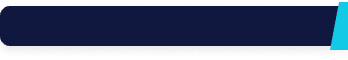Keburu Sebar
loading...

H Irwan SIP, MP, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat. Foto: Ist
A
A
A
H Irwan SIP, MP
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat
KORONA Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar hampir 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat global pun heboh, panik, dan berfokus membendung penyebarannya. Ketika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak lagi bebas dari virus korona, Senin (2/3/2020), dimulailah rasa kepanikan, waswas, bahkan muncul banyak pretensi di kalangan masyarakat.
Kasak-kusuk Indonesia terjangkit Covid-19 sejak Januari 2020 menyeruak ke publik. Sebulan setelah endemi di Wuhan, China, dan akhirnya WHO menyatakan pandemi. Hal itu dikatakan bukan dari pemangku negeri yang berada di Istana Negara, justru Balai Kota yang jaraknya hanya sejengkal dari Istana Negara, yakni Gubernur Anies Baswedan.
Anies mengatakan perangkat pemerintahannya sudah persiapan menghadapi wabah virus korona sejak Januari 2020. Tapi, semua itu dianggap politis sehingga saling bantah terjadi.
Sebetulnya kalau pemerintah pusat serius, pernyataan Anies itu bisa dijadikan masukan dan telaah lebih jauh. Ibarat sedia payung sebelum hujan. Nah , sekarang hujannya deras, banjir bandang, perahu pun hampir pecah. Terus mau apa lagi? Tapi, rakyat tetap optimistis di tengah rasa pesimistis. Percaya dan panik.
Menukil hasil analisis Drone Emprit; lembaga yang memonitor serta menganalisis media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data; ada dua persepsi publik yang muncul dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah, yakni ketakutan (fear ) dan kepercayaan (trust ). Drone Emprit menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah soal trust (kepercayaan) publik kepada pemerintah. Bukan soal fear atau kepanikan saat pemerintah membuka data yang transparan.
Dari hasil analisis itu, seyogianya pemerintah jujur dan transparan atas data penanganan Covid-19, bukan malah ditutupi, tidak transparan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menyebabkan kepanikan. Pun kepercayaan publik ini dibutuhkan supaya terjalin kerja sama antara warga dan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Tidak bisa bekerja sendiri.
Guna membangun kepercayaan publik yang telanjur kikis, sebaiknya pemerintah membangun transparansi informasi. Bukan sebaliknya, komunikasi buruk terjadi. Mirisnya, dilakukan kabinet pimpinan Presiden Jokowi. Contohnya, soal mudik bagi masyarakat. Setidaknya Presiden Jokowi dengan tegas melalui media massa publik melarang mudik di tengah pandemi. Bukan menggantung dengan imbauan saja. Ujung-ujungnya bisa diralat bawahannya.
Seperti apa yang digambarkan Wijayanto, peneliti Center for Media and Democracy, LP3ES, petaka karena kata sehingga pandemi semakin mewabah. Masih mengutip penelitian LP3ES, komunikasi buruk masih ditunjukkan pemerintah dalam krisis pandemi Covid-19 ini.
Merujuk penelitian itu, dalam tempo kurang dari 100 hari sejak pandemi Covid-19 menjadi isu dan ancaman di Indonesia mulai akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Presiden Jokowi dan kabinetnya. Pertama , 13 pernyataan blunder di masa prakrisis periode Januari-akhir Februari 2020, penelitian LP3ES menyebutkan bahwa pemerintah tidak serius menanggapi Covid-19, justru menyepelekan dan menolak seakan korona masuk ke Indonesia, meskipun peringatan telah ada sejak Januari 2020.
Pernyataan blunder itu dilakukan mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkopolhukam Machfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Whisnutama, dan terakhir Dirjen Perhubungan Udara Novi Riyanto.
Pernyataan blunder pemerintah ini justru menyebabkan kepanikan terhadap masyarakat dan membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah terjadi serta berdampak dalam sistem kesehatan nasional gagap sejak awal untuk menangani wabah korona.
Kedua , empat pernyataan blunder di awal krisis di periode awal Maret, di mana LP3ES menilai blunder pertama yakni keterlambatan Presiden Jokowi mengumumkan korona sudah menjangkit di Indonesia, di mana peringatan ini sudah terjadi sejak Januari 2020. Lalu, blunder kedua yakni inkonsistensi Juru Bicara Ahmad Yurianto yang membantah bahwa pasien pertama Covid-19 itu berasal dari Cianjur sejak akhir Februari 2020, namun kemudian bantahan tersebut diralat.
Kemudian Presiden Jokowi membuat pernyataan blunder lagi, sudah diumumkan ada pasien positif korona masih saja menggaungkan soal diskon tiket pesawat guna mendorong sektor pariwisata. Dan, terakhir, Wapres masih juga meremehkan bahayanya virus korona ini dengan menyebut minum susu kuda liar.
Ketiga , 20 pernyataan blunder di masa krisis (awal Maret-sekarang), menurut catatan LP3ES, blunder terbanyak terjadi dalam polemik mudik. Ada sembilan pernyataan yang keliru yang dikeluarkan enam pejabat negara. Presiden awalnya melarang mudik dan diamini oleh Jubir Presiden, Jubir Covid-19, dan Mensesneg. Selang kemudian diralat oleh bawahannya, yakni Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman dan Investasi. Ironisnya, Presiden juga ikut meralat pernyataan larangan mudik ini.
Kini, persebaran wabah korona kian luas. Setelah menganggap enteng, gelagapan ketika makin banyak terjangkit. Penelitian itu membuktikan tak satu suara pemerintah pusat menanganinya. Ditambah lagi koordinasi dengan pemerintah daerah pun berantakan. Ironisnya lagi, rumah sakit pun tak siap.
PSBB Birokratis
Meski pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, sayangnya tak dibarengi dengan pemaparan strategi yang transparan dan komprehensif guna membangun trust dan optimisme masyarakat. Malah jadi waswas. Sensor informasi itu sebabnya. Sebagai anggota parlemen yang dijamin konstitusi, terus berpikir, bersuara dan bertindak, apa yang menjadi harapan rakyat dalam menghadapi pandemi. Harapan itu adalah cepat berlalu pandemi ini, di samping membaiknya situasi ekonomi.
Karantina wilayah, suara pertama yang aku gemakan di media. Mengingat konstitusi memandatkan karantina wilayah ini, yakni UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 di mana negara memberikan jaminan hidup kepada rakyatnya. Namun, akhirnya, Presiden Jokowi mengumumkan langkah diambil dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mengacu pada mengacu UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 59.
Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 sudah terbit, turunan dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 terkait pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Di Permenkes ini diatur bagaimana prosedur permohonan pemda ke pemerintah pusat jika ingin daerahnya diputuskan sebagai PSBB oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan. Ini sangat birokrasi. Meski dalam Permenkes telah disebutkan akan dikerjakan dalam waktu dua hari, kenyataannya pemerintah daerah akan mengalami kendala dalam melengkapi berkas yang kurang.
Jika birokrasi memperlambat integrasi penanganan, bisa jadi akan sulit memutus rantai penyebaran virus. Dikhawatirkan virusnya keburu berkembang biak di seluruh tubuh rakyat Indonesia, akibat birokratisnya PSBB ini. Dengan alasan kemanusiaan tersebut, sebagai wakil rakyat tetap mendesak pemerintah untuk memutuskan lockdown alias karantina wilayah agar situasinya tidak seperti sekarang ini.
Bisa dibayangkan, masyarakat terus diminta stay di rumah tapi tidak dijamin biaya hidupnya. Masalah lain pun akan timbul, seperti kriminalitas, sosial, ekonomi seperti efek domino dihadapi pemerintah. Maka dari itu, pembatasan sosial skala besar seperti sekarang ini mana mungkin pemerintah bisa bertindak tegas kalau masyarakat keluar rumah tetapi hidup tetap tidak dijamin.
Selain itu, pemerintah daerah mau menutup pelabuhan, bandara, Stasiun KA, dan terminal dengan bertujuan karantina daerah atau penyekatan orang datang ke daerah zona merah Covid-19 pun tetap tidak bisa karena semua kewenangan pusat.
Sisi lain, pertanyaan publik muncul, mengapa Menteri Kesehatan sebagai penanggung jawab kedaruratan kesehatan harus menunggu permohonan dari pemerintah daerah untuk menerapkan PSBB? Padahal, data saat ini zona merah Covid-19 sudah menjangkit hampir 24 provinsi di Indonesia. Dalam keadaan darurat justru seharusnya top down. Tegas dari atas. Bukan bottom up yang masih birokratis. Kalau tergantung daerah, mungkin enggak perlu ada status kedaruratan sekalipun pemda sudah pada karantina wilayah sendiri, bukan PSBB lagi.
Mungkin penyebabnya pemerintah pusat tidak ingin menanggung biaya PSBB. Tergantung pada kesiapan daerah. Daerah yang mengusulkan, tentunya. Kalau begini, rakyat sudah jatuh tertimpa tangga. (*)
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat
KORONA Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar hampir 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat global pun heboh, panik, dan berfokus membendung penyebarannya. Ketika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak lagi bebas dari virus korona, Senin (2/3/2020), dimulailah rasa kepanikan, waswas, bahkan muncul banyak pretensi di kalangan masyarakat.
Kasak-kusuk Indonesia terjangkit Covid-19 sejak Januari 2020 menyeruak ke publik. Sebulan setelah endemi di Wuhan, China, dan akhirnya WHO menyatakan pandemi. Hal itu dikatakan bukan dari pemangku negeri yang berada di Istana Negara, justru Balai Kota yang jaraknya hanya sejengkal dari Istana Negara, yakni Gubernur Anies Baswedan.
Anies mengatakan perangkat pemerintahannya sudah persiapan menghadapi wabah virus korona sejak Januari 2020. Tapi, semua itu dianggap politis sehingga saling bantah terjadi.
Sebetulnya kalau pemerintah pusat serius, pernyataan Anies itu bisa dijadikan masukan dan telaah lebih jauh. Ibarat sedia payung sebelum hujan. Nah , sekarang hujannya deras, banjir bandang, perahu pun hampir pecah. Terus mau apa lagi? Tapi, rakyat tetap optimistis di tengah rasa pesimistis. Percaya dan panik.
Menukil hasil analisis Drone Emprit; lembaga yang memonitor serta menganalisis media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data; ada dua persepsi publik yang muncul dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah, yakni ketakutan (fear ) dan kepercayaan (trust ). Drone Emprit menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah soal trust (kepercayaan) publik kepada pemerintah. Bukan soal fear atau kepanikan saat pemerintah membuka data yang transparan.
Dari hasil analisis itu, seyogianya pemerintah jujur dan transparan atas data penanganan Covid-19, bukan malah ditutupi, tidak transparan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menyebabkan kepanikan. Pun kepercayaan publik ini dibutuhkan supaya terjalin kerja sama antara warga dan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Tidak bisa bekerja sendiri.
Guna membangun kepercayaan publik yang telanjur kikis, sebaiknya pemerintah membangun transparansi informasi. Bukan sebaliknya, komunikasi buruk terjadi. Mirisnya, dilakukan kabinet pimpinan Presiden Jokowi. Contohnya, soal mudik bagi masyarakat. Setidaknya Presiden Jokowi dengan tegas melalui media massa publik melarang mudik di tengah pandemi. Bukan menggantung dengan imbauan saja. Ujung-ujungnya bisa diralat bawahannya.
Seperti apa yang digambarkan Wijayanto, peneliti Center for Media and Democracy, LP3ES, petaka karena kata sehingga pandemi semakin mewabah. Masih mengutip penelitian LP3ES, komunikasi buruk masih ditunjukkan pemerintah dalam krisis pandemi Covid-19 ini.
Merujuk penelitian itu, dalam tempo kurang dari 100 hari sejak pandemi Covid-19 menjadi isu dan ancaman di Indonesia mulai akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Presiden Jokowi dan kabinetnya. Pertama , 13 pernyataan blunder di masa prakrisis periode Januari-akhir Februari 2020, penelitian LP3ES menyebutkan bahwa pemerintah tidak serius menanggapi Covid-19, justru menyepelekan dan menolak seakan korona masuk ke Indonesia, meskipun peringatan telah ada sejak Januari 2020.
Pernyataan blunder itu dilakukan mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkopolhukam Machfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Whisnutama, dan terakhir Dirjen Perhubungan Udara Novi Riyanto.
Pernyataan blunder pemerintah ini justru menyebabkan kepanikan terhadap masyarakat dan membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah terjadi serta berdampak dalam sistem kesehatan nasional gagap sejak awal untuk menangani wabah korona.
Kedua , empat pernyataan blunder di awal krisis di periode awal Maret, di mana LP3ES menilai blunder pertama yakni keterlambatan Presiden Jokowi mengumumkan korona sudah menjangkit di Indonesia, di mana peringatan ini sudah terjadi sejak Januari 2020. Lalu, blunder kedua yakni inkonsistensi Juru Bicara Ahmad Yurianto yang membantah bahwa pasien pertama Covid-19 itu berasal dari Cianjur sejak akhir Februari 2020, namun kemudian bantahan tersebut diralat.
Kemudian Presiden Jokowi membuat pernyataan blunder lagi, sudah diumumkan ada pasien positif korona masih saja menggaungkan soal diskon tiket pesawat guna mendorong sektor pariwisata. Dan, terakhir, Wapres masih juga meremehkan bahayanya virus korona ini dengan menyebut minum susu kuda liar.
Ketiga , 20 pernyataan blunder di masa krisis (awal Maret-sekarang), menurut catatan LP3ES, blunder terbanyak terjadi dalam polemik mudik. Ada sembilan pernyataan yang keliru yang dikeluarkan enam pejabat negara. Presiden awalnya melarang mudik dan diamini oleh Jubir Presiden, Jubir Covid-19, dan Mensesneg. Selang kemudian diralat oleh bawahannya, yakni Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman dan Investasi. Ironisnya, Presiden juga ikut meralat pernyataan larangan mudik ini.
Kini, persebaran wabah korona kian luas. Setelah menganggap enteng, gelagapan ketika makin banyak terjangkit. Penelitian itu membuktikan tak satu suara pemerintah pusat menanganinya. Ditambah lagi koordinasi dengan pemerintah daerah pun berantakan. Ironisnya lagi, rumah sakit pun tak siap.
PSBB Birokratis
Meski pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, sayangnya tak dibarengi dengan pemaparan strategi yang transparan dan komprehensif guna membangun trust dan optimisme masyarakat. Malah jadi waswas. Sensor informasi itu sebabnya. Sebagai anggota parlemen yang dijamin konstitusi, terus berpikir, bersuara dan bertindak, apa yang menjadi harapan rakyat dalam menghadapi pandemi. Harapan itu adalah cepat berlalu pandemi ini, di samping membaiknya situasi ekonomi.
Karantina wilayah, suara pertama yang aku gemakan di media. Mengingat konstitusi memandatkan karantina wilayah ini, yakni UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 di mana negara memberikan jaminan hidup kepada rakyatnya. Namun, akhirnya, Presiden Jokowi mengumumkan langkah diambil dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mengacu pada mengacu UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 59.
Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 sudah terbit, turunan dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 terkait pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Di Permenkes ini diatur bagaimana prosedur permohonan pemda ke pemerintah pusat jika ingin daerahnya diputuskan sebagai PSBB oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan. Ini sangat birokrasi. Meski dalam Permenkes telah disebutkan akan dikerjakan dalam waktu dua hari, kenyataannya pemerintah daerah akan mengalami kendala dalam melengkapi berkas yang kurang.
Jika birokrasi memperlambat integrasi penanganan, bisa jadi akan sulit memutus rantai penyebaran virus. Dikhawatirkan virusnya keburu berkembang biak di seluruh tubuh rakyat Indonesia, akibat birokratisnya PSBB ini. Dengan alasan kemanusiaan tersebut, sebagai wakil rakyat tetap mendesak pemerintah untuk memutuskan lockdown alias karantina wilayah agar situasinya tidak seperti sekarang ini.
Bisa dibayangkan, masyarakat terus diminta stay di rumah tapi tidak dijamin biaya hidupnya. Masalah lain pun akan timbul, seperti kriminalitas, sosial, ekonomi seperti efek domino dihadapi pemerintah. Maka dari itu, pembatasan sosial skala besar seperti sekarang ini mana mungkin pemerintah bisa bertindak tegas kalau masyarakat keluar rumah tetapi hidup tetap tidak dijamin.
Selain itu, pemerintah daerah mau menutup pelabuhan, bandara, Stasiun KA, dan terminal dengan bertujuan karantina daerah atau penyekatan orang datang ke daerah zona merah Covid-19 pun tetap tidak bisa karena semua kewenangan pusat.
Sisi lain, pertanyaan publik muncul, mengapa Menteri Kesehatan sebagai penanggung jawab kedaruratan kesehatan harus menunggu permohonan dari pemerintah daerah untuk menerapkan PSBB? Padahal, data saat ini zona merah Covid-19 sudah menjangkit hampir 24 provinsi di Indonesia. Dalam keadaan darurat justru seharusnya top down. Tegas dari atas. Bukan bottom up yang masih birokratis. Kalau tergantung daerah, mungkin enggak perlu ada status kedaruratan sekalipun pemda sudah pada karantina wilayah sendiri, bukan PSBB lagi.
Mungkin penyebabnya pemerintah pusat tidak ingin menanggung biaya PSBB. Tergantung pada kesiapan daerah. Daerah yang mengusulkan, tentunya. Kalau begini, rakyat sudah jatuh tertimpa tangga. (*)
(jon)