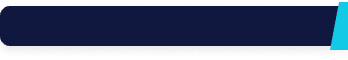Kisah Pahlawan: Syarif Hidayat, Mengajar Madrasah Berbekal Dua Liter Beras
loading...
A
A
A
Jika ada sesuatu yang membuatnya bertahan hingga saat ini, bisa jadi itu karena wasiat dari Ajengan Hanafi, begitu ia biasa menyapa gurunya. Kata-kata itu pula yang memantapkan hatinya untuk tetap mengajarkan agama, menyiarkan Islam dan membina akhlak masyarakat kampung Cilulumpang. Syarif pun mengakui tantangannya saat ini lebih berat dibanding masa-masa sebelumnya, terlihat dari persentasi jumlah santri yang tinggal di kobong (asrama).
Santri yang tinggal di kobong ini biasanya bukan sekadar mengaji di madrasah diniyah, melainkan juga ngaji kitab-kitab yang diajarkan saat subuh dan malam hari, dan jumlahnya terus berkurang. “Kalau dulu, ada sekitar 30– 40 an santri. Anak sekarang uangnya ada, bukunya terbeli, eh anaknya yang nggak mau,” tukasnya.
Ia membandingkan santri zaman sekarang dengan dulu. Dahulu warga desa biasa berjalan kaki, banyak juga dari warga kampung lain dan berkilo-kilo jauhnya, tetap datang ke madrasah untuk ngaji. “Sekarang sudah pada pakai motor, malah nggak ada nginep di kobong. Ngaji. Alasannya takut ketinggalan sekolah. Padahal mah dulu jalan kaki biasa,” tambahnya.
Ia berusaha tetap bijak melihat ini. Tantangannya kini berbeda. Namun, hal itu tidak pernah menyurutkan langkahnya untuk tetap bertahan mengajar. Bahkan, ia bercita-cita mendirikan madrasah tingkat wustho (menengah). “Kalau ada madrasah tsanawiyah (MTs), anak-anak bisa belajar agama lebih banyak lagi. tidak perlu jauh ke daerah lain. Tidak perlu jalan kaki 3 km untuk ke SMP terdekat di kecamatan,” ujarnya.
Mendirikan MTs tentu tidak mudah, apalagi selama 35 tahun Madrasah Miftahul Aulad berdiri belum memiliki akta resmi, sebuah yayasan sebagai payung kelembagaan madrasah. Selama ini, akta masih menginduk ke yayasan orang lain dan untuk madrasah yang ia pimpin sedang dipersiapkan legalitasnya.
Belakangan ia berpikir, bagaimana bisa memperbaiki kobong yang sudah mulai rusak berat itu dan -walaupun para guru itu tidak pernah mengeluh–kesejahteraan guru madrasah itu. Ketiga anaknya juga sudah belajar di perguruan tinggi. Ia berharap anaknya bakal menjadi generasi penerus, mengelola madrasah dan mendirikan MTs sebagaimana yang ia idamkan. Tentunya jika ada bantuan dari pemerintah atau lembaga lain, akan cukup membantu. Namun menurutnya, ada atau tidaknya yayasan tidak akan berpengaruh pada proses belajar-mengajar di Miftahul Aulad.
Toh, selama ini kegiatan terus berjalan dan guru-guru terus akan berjuang bersama membangun masyarakat. “Sampai semampunya, saya tidak mau kalah. Sampai liang lahat, saya tidak akan berhenti belajar dan mengajar sesuai perintah agama,” ujarnya.
Tulisan ini diambil dari buku “Mendidik Tanpa Pamrih: Kisah para Pejuang Pendidikan Islam” yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag, tahun 2015.
Santri yang tinggal di kobong ini biasanya bukan sekadar mengaji di madrasah diniyah, melainkan juga ngaji kitab-kitab yang diajarkan saat subuh dan malam hari, dan jumlahnya terus berkurang. “Kalau dulu, ada sekitar 30– 40 an santri. Anak sekarang uangnya ada, bukunya terbeli, eh anaknya yang nggak mau,” tukasnya.
Ia membandingkan santri zaman sekarang dengan dulu. Dahulu warga desa biasa berjalan kaki, banyak juga dari warga kampung lain dan berkilo-kilo jauhnya, tetap datang ke madrasah untuk ngaji. “Sekarang sudah pada pakai motor, malah nggak ada nginep di kobong. Ngaji. Alasannya takut ketinggalan sekolah. Padahal mah dulu jalan kaki biasa,” tambahnya.
Ia berusaha tetap bijak melihat ini. Tantangannya kini berbeda. Namun, hal itu tidak pernah menyurutkan langkahnya untuk tetap bertahan mengajar. Bahkan, ia bercita-cita mendirikan madrasah tingkat wustho (menengah). “Kalau ada madrasah tsanawiyah (MTs), anak-anak bisa belajar agama lebih banyak lagi. tidak perlu jauh ke daerah lain. Tidak perlu jalan kaki 3 km untuk ke SMP terdekat di kecamatan,” ujarnya.
Mendirikan MTs tentu tidak mudah, apalagi selama 35 tahun Madrasah Miftahul Aulad berdiri belum memiliki akta resmi, sebuah yayasan sebagai payung kelembagaan madrasah. Selama ini, akta masih menginduk ke yayasan orang lain dan untuk madrasah yang ia pimpin sedang dipersiapkan legalitasnya.
Belakangan ia berpikir, bagaimana bisa memperbaiki kobong yang sudah mulai rusak berat itu dan -walaupun para guru itu tidak pernah mengeluh–kesejahteraan guru madrasah itu. Ketiga anaknya juga sudah belajar di perguruan tinggi. Ia berharap anaknya bakal menjadi generasi penerus, mengelola madrasah dan mendirikan MTs sebagaimana yang ia idamkan. Tentunya jika ada bantuan dari pemerintah atau lembaga lain, akan cukup membantu. Namun menurutnya, ada atau tidaknya yayasan tidak akan berpengaruh pada proses belajar-mengajar di Miftahul Aulad.
Toh, selama ini kegiatan terus berjalan dan guru-guru terus akan berjuang bersama membangun masyarakat. “Sampai semampunya, saya tidak mau kalah. Sampai liang lahat, saya tidak akan berhenti belajar dan mengajar sesuai perintah agama,” ujarnya.
Tulisan ini diambil dari buku “Mendidik Tanpa Pamrih: Kisah para Pejuang Pendidikan Islam” yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag, tahun 2015.
(mpw)